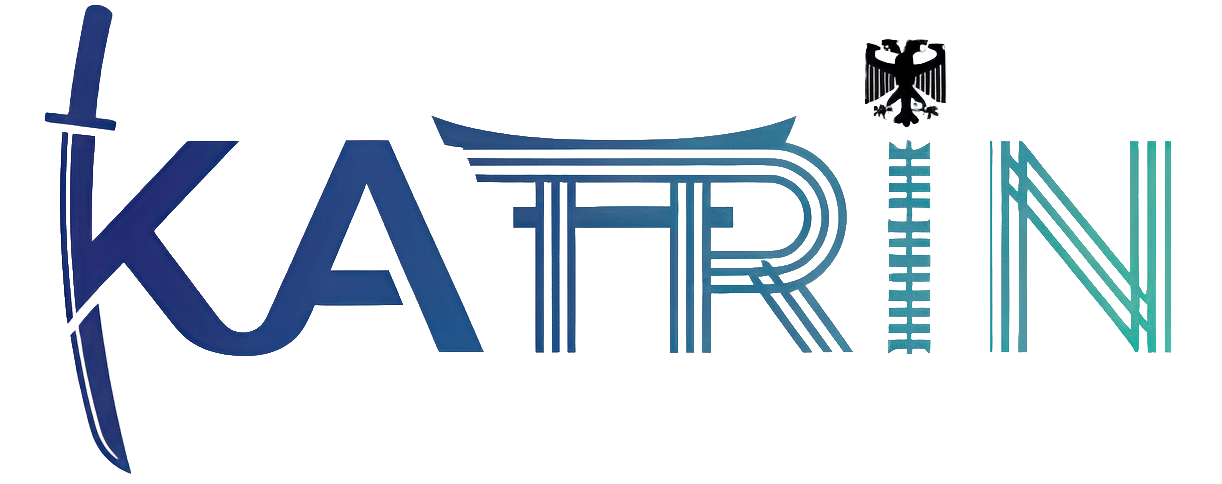Pontianak – Pesona Khatulistiwa
Ada sesuatu yang selalu menggoda dari kota-kota yang tumbuh di tepian sungai besar. Kota-kota ini menyimpan denyut kehidupan yang berbeda: lebih lambat, intim, penuh kisah yang meresap ke dalam jiwa.
Pontianak, kota khatulistiwa di jantung Kalimantan Barat, adalah salah satunya. Dari udara, saya melihat garis panjang Sungai Kapuas, meliuk bagai syair tua yang diguratkan tangan alam. Saat roda pesawat menyentuh landasan Bandar Udara Internasional Supadio, langkah pertama membawa saya ke tepian Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia sekaligus nadi kehidupan kota ini.
“Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia. Ku berdoa untuk dia yang kurindukan…” Lagu Jangan Lupakan dari Nidji mengalun mengiringi langkah saya keluar dari pesawat. Tepat sebulan setelah dia pulang, saya mengunjungi kota ini. Sebenarnya saya ingin menuliskannya di situs utama saya, tapi tampaknya, semua ini akan cocok untuk berada di sini.
Saya memilih duduk di salah satu kafe yang menghadap ke tepian sungai. Dari sini, air cokelat keemasan memantulkan cahaya sore dengan lembut. Perahu klotok berlalu-lalang, membawa penumpang, hasil bumi, dan cerita-cerita kecil yang menjahit kehidupan sehari-hari. Anak-anak melompat riang dari dermaga, tawa mereka bersaing dengan bunyi cipratan air. Ibu-ibu menjemur ikan asin sambil berceloteh ringan, sementara para bapak menyalakan lampu perahu, ditemani aroma kopi bubuk yang mengepul dari warung kecil di tepi sungai.

Menjelang malam, saya naik ke perahu wisata, menyusuri Kapuas yang makin syahdu. Angin sungai mengusap lembut wajah, membawa aroma kayu basah dan asap dupa dari deretan rumah-rumah di tepiannya. Kota perlahan menyala, jembatan-jembatan berkilau, sementara langit menunjukan warna ungu dramatis. Di momen itu, Pontianak terasa seperti kota yang tahu cara merayu, dengan kesederhanaan yang penuh rasa.
Keesokan paginya, saya menuju Istana Kadriah, istana kuning peninggalan Kesultanan Pontianak. Di dalamnya, ruang-ruang luas menyimpan perabot antik, foto keluarga kerajaan, dan aura sejarah yang pekat. Pemandu bercerita tentang Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, pendiri kota ini pada abad ke-18. Saya melangkah perlahan di koridor kayu yang berderit, sesekali terdengar derit lembut dari lantainya.
Istana ini bukan sekadar bangunan; melainkan cermin sejarah yang masih bernapas. Warna kuning pada fasadnya melambangkan martabat Melayu. Koleksi pusaka hingga singgasana sultan menghadirkan potongan waktu yang seolah membeku namun tetap hidup.

Dari jejak sejarah, perjalanan berlanjut jauh ke Kapuas Hulu, menuju Danau Sentarum. Dari Pontianak, saya terbang menuju Putussibau. Delapan jam perjalanan darat dari Putussibau terasa panjang, tapi setiap kilometer menghadirkan pemandangan yang menenangkan: hutan tropis, desa-desa kayu, serta kabut tipis di perbukitan.
Sesampainya di Taman Nasional Danau Sentarum, lelah sirna seketika. Danau Sentarum di malam hari bagai dunia lain, tenang dan seolah sakral. Airnya memantulkan cahaya bulan, berkali seperti kaca hitam yang ditaburi perak. Di kejauhan, suara jangkrik dan katak bersahut-sahutan, dipadu dengn desir angin yang menyapu pucuk hutan rawa.
Rumah-rumah panggung nelayan tampak berpendar temaram dari lampu minyak, memantulkan siluet hitam di tepi danau. Tak hanya taman nasional, air danau ini menjadi habitat ikan arwana merah langka, ekosistemnya menjadi rumah bagi orangutan hingga bekantan dan membuat danau ini menjelma menjadi cagar biosfer UNESCO.
Pagi hari berikutnya, saya berperahu kecil menyusuri air yang tenang. Danau luas ini memantulkan langit, dikelilingi hutan rawa dan pulau-pulau kecil. Saat musim hujan, seluruh wilayah tergenang; namun di musim kemarau berubah menjadi padang rumput yang luas, keajaiban yang sungguh sulit ditemui ditempat lain.
Hari terakhir saya dedikasikan untuk Singkawang, kota kecil tiga jam perjalanan dari Pontianak. Singkawang adalah “Kota Seribu Kuil”, rumah bagi populasi Tionghoa terbesar di Indonesia. Kota ini memikat dengan harmoni budaya Tionghoa, Melayu, dan Dayak.
Lampion merah bergelantungan di jalan utama, memberi nuansa meriah sekaligus hangat. Saya singgah di Vihara Tri Dharma Bumi Raya, kelenteng terbesar dan tertua yang berdiri megah. Pintu merah menjulang, ukiran naga meluk, asap dupa melayang-layang membawa lantunan do’a yang tak berujung. Di sini, saya merasakan ketenangan yang dalam. Ritual sederhana para jemaat, bunyi lonceng bergema lembut, serta cahaya lilin yang berkedip-kedip dan berpendar menghadirkan suasana magis.
Perjalanan saya ditutup di Pulau Lemukutan, surga tropis yang nyaris tak tersentuh. Dari dermaga Singkawang, perahu membawa saya satu jam menyeberang laut biru. Pulau ini menyambut dengan pasir putih halus, air sebening kristal, dan terumbu karang berwarna-warni. Dengan puluhan jenis karang yang dimilikinya, Lemukutan adalah surganya snorkeling. Menariknya, pulau ini bebas dari mobil, menghadirkan kedamaian tanpa polusi. Saya berjalan menyusuri pantai, membiarkan ombak membasahi kaki, sementara langit sore menutup hari dengan kanvas jingga.

Di Lemukutan, waktu seakan berhenti. Saya duduk sendirian di pasir, mendengar lagu laut, membiarkan ingatan empat hari terakhir berputar: riuh Kapuas, sunyi Sentarum, hangat Singkawang, dan teduh Lemukutan. Semuanya kini terpatri dalam jiwa.
Di antara deru mesin pesawat yang membawa saya pulang, pandangan saya menembus jendela, menuju hijau hutan Kalimantan yang membentang seperti untaian zamrud, menyadari betapa pengalaman seperti ini menjadi bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan untuk terus memandang, merayakan bahagia dan mensyukuri kehilangan, menerima pertemuan dengan segala cerita uniknya, dan kadang kala kesedihan hati itu bukanlah benar-benar akhir.