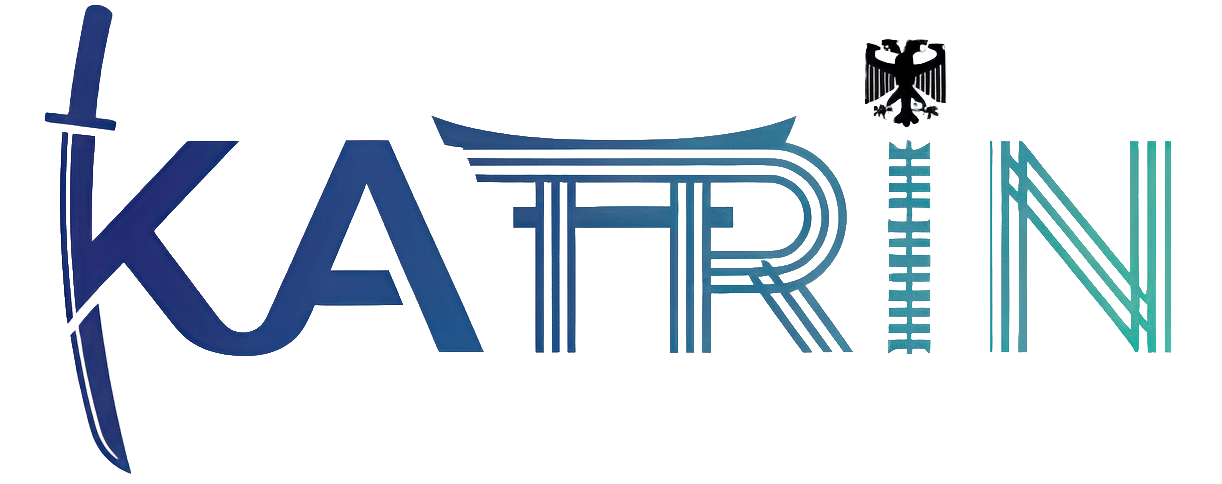Makassar
Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Sultan Hasanuddin, terlintas dalam benak saya pelajaran tentang sejarah maritim Nusantara. Saya datang dengan penuh rasa ingin tahu, ingin mengenal kota pelaut Bugis-Makassar ini, bukan hanya lewat cerita, tetapi dengan pengalaman yang bisa langsung dirasakan.
Saat fajar menyingsing, nelayan mulai melempar jaringnya, menjaga tradisi yang menjadi sumber kehidupan di Makassar.
Makassar, yang dahulu dikenal sebagai Gowa-Tallo, adalah panggung utama perdagangan dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Dengan kebijakan “pintu terbuka” dan posisi yang sangat strategis, kota ini tumbuh menjadi bandar niaga internasional yang ramai. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, hingga Eropa menjadikan pelabuhannya sebagai titik transit krusial di jalur rempah, tempat komoditas berharga seperti cengkeh dan pala dari Maluku dipertukarkan.
Bersiap untuk menyelami sisa-sisa kejayaan tersebut, hari pertama saya dimulai di Pelabuhan Paotere, yang hingga kini masih menyimpan jejak para pelaut Bugis di masa lampau. Deretan kapal pinisi berlabuh di dermaga yang sudah berusia ratusan tahun ini, tampak gagah dengan warna kayunya yang semakin pekat dimakan waktu, seperti prajurit tua yang berpengalaman.
Karena sudah sore, matahari terasa hangat dan tidak terlalu menyengat. Saya berjalan melewati para nelayan yang sibuk mengangkat jaring dengan tangan mereka yang terampil. Beberapa di antara mereka menyapa dengan ramah hingga saya pun menyempatkan diri untuk berbincang sejenak. Dari sini, katanya, pengunjung juga bisa menyewa perahu nelayan untuk berkeliling atau sekadar menikmati pemandangan laut yang terbentang luas.
Sebelum pulang, saya mampir ke tempat pelelangan ikan tak jauh dari dermaga. Deretan ikan segar di sana membuat saya memutuskan untuk makan malam lebih awal. Saya memilih beberapa ekor ikan kerapu dan cumi, lalu membawanya ke warung lokal untuk dimasak langsung. Tak lama kemudian, sepiring ikan bakar pedas manis tersaji di meja-sederhana, segar, dan penuh cita rasa.
Menjelang senja, tempat ini berubah menjadi lokasi yang menenangkan, tempat terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam di balik siluet kapal pinisi, sembari mendengar deburan ombak pelan yang memantulkan warna oranye keemasan di permukaan air, seolah-olah laut dan langit Makassar bersatu untuk menutup hari itu.
Setelah sehari menikmati denyut kehidupan di pelabuhan tua, keesokan paginya saya memutuskan untuk mencari sisi lain Makassar, bukan yang bising dan beraroma garam laut, melainkan yang tenang dan dikelilingi alam hijau. Saya pun menempuh perjalanan sekitar satu jam ke arah utara, menuju Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. Dalam bahasa Bugis, “rammang” artinya awan atau kabut-nama yang begitu pas, karena sesampainya saya di sana, kabut tipis menggantung rendah di atas gugusan batu karst raksasa yang menjulang tinggi.
Saya menaiki perahu kecil bermesin tempel, menyusuri Sungai Pute yang tenang. Airnya memantulkan bayangan langıt dan batu-batu kapur. Sesekali suara burung terdengar menggema di kejauhan. Saya pun terpesona pada ketenangan yang ditawarkan tempat ini-yang kini diakui oleh UNESCO sebagai salah satu gugusan karst terbesar di dunia setelah Shilin Karst Forest di China dan Tsingy de Bemaraha National Park di Madagaskar.
Kampung Berua, yang merupakan landmark utama dari kawasan wisata Rammang-Rammang, menyuguhkan suasana pedesaan dengan rumah-rumah panggung tradisional. Warganya hidup dari bertani dan beternak ikan, juga mengelola perahu wisata untuk membawa pengunjung berkeliling menikmati keindahan tebing karst yang menjulang tinggi. Dengan udara yang sejuk dan hamparan sawah yang luas dan hijau, tempat ini ideal bagi pengunjung yang ingin melarikan diri dari hiruk pikuk kota.
Agar dapat melihat panorama pemandangan sekitar Kampung Berua, Rammang-Rammang, dan Sungai Pute dari sudut pandang berbeda, saya membawa langkah saya untuk sedikit mendaki ke Padang Ammarung. Di titik tertinggi, saya berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu duduk di atas batu besar sambil memandangi lembah-rasanya seperti menyaksikan lukisan yang hidup.
Pada hari ketiga, saya ingin menikmati suhu yang lebih sejuk di dataran tinggi. Sekitar 60 km dari Makassar, jalanan berliku membawa saya ke Malino, Kabupaten Gowa. Begitu turun dari mobil, angin dingin langsung menyergap-terasa begitu bersih dan menyegarkan.
Hamparan kebun teh menyapa mata, berlapis-lapis menyelimuti lereng bukit dalam gradasi warna hijau yang menenangkan. Para pemetik teh bergerak perlahan sambil bercengkerama, sementara tangan mereka yang cekatan memetik pucuk-pucuk muda. Sembari duduk di warung kecil, saya menyesap teh hangat sambil menyaksikan Gunung Bawakaraeng yang berdiri megah, menjadi latar belakang sempurna.
Kebun Teh Malino yang terbentang luas menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati udara pegunungan yang menyegarkan.
Setelah puas beristirahat sambil menikmati pemandangan, saya berjalan kaki menelusuri jalan setapak di antara barisan pohon teh. Aroma tanah basah dan daun teh menciptakan terapi alami, sebuah pelarian damai bagi seluruh indra.
Keesokan harinya, untuk mengakhiri perjalanan, rasanya tak lengkap jika tidak mengunjungi laut di kota pesisir ini. Saya menaiki perahu motor kecil dari Pantai Losari menuju Pulau Samalona, sebuah pulau mungil yang dapat dicapai hanya dalam waktu sekitar dua puluh menit. Semakin mendekat, air laut perlahan berubah menjadi gradasi biru muda dan hijau toska, begitu jernih hingga memungkinkan saya melihat dasar laut yang dipenuhi terumbu karang dan ikan-ikan warna-warni.
Meski luasnya hanya beberapa hektare, pulau kecil ini memancarkan pesona tropis yang memikat: hamparan pasir putih yang lembut, deretan pohon kelapa yang melambai diterpa angin, serta suasana tenang yang mengundang. Saya berjalan tanpa alas kaki menyusuri tepi pantai, membiarkan air asin membasahi kulit dan butiran pasir halus mengalir di sela jari.
Beberapa wisatawan tampak snorkeling di perairan dangkal, sementara anak-anak lokal bermain air sambil tertawa riang. Saat angin laut berembus lembut, saya tahu inilah momen yang ingin saya simpan: ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan yang sederhana.
Empat hari di Makassar terasa singkat, tapi penuh warna. Saya menemukan sejarah yang hidup di Paotere, keindahan alam yang menakjubkan di Rammang-Rammang, kesejukan pegunungan di Malino, dan pesona laut biru di Samalona. Setiap sudutnya punya cara sendiri untuk memikat dan selalu mengundang untuk kembali.
Mungkin suatu saat saya akan kembali ke sini, entah sendiri, atau bersama orang yang ingin saya ajak untuk kembali berpetualang. Atau mungkin juga takdir kami sampai di sini saja. Tetapi, Makassar akan tetap saya ingat sebagai tempat yang membantu saya untuk kembali berdiri tegak dan menikmati sisa hidup saya.